Acapkali kita disajikan berita tentang dugaan kasus malapraktik yang melibatkan tenaga kesehatan, terutama dilakukan oleh dokter, yang terjadi di berbagai rumah sakit belakangan ini.
Tidak sedikit masyarakat mengeluhkan buruknya pelayanan dan manajemen rumah sakit tempatnya dirawat. Beberapa diantaranya harus sampai pada proses hukum yang melelahkan.
Hampir semua lini pelayanan tak luput dari terjangan ketidakpuasan masyarakat, mulai dari penerimaan pertama pasien di Unit Gawat Darurat atau Poliklinik umum, pelayanan dokter dan asuhan perawatan, hingga pada masalah penebusan biaya selama perawatan dan pelayanan pasien di rumah sakit. Inilah realitas rumah sakit kita.
Belitan dana dan relatif longgarnya pengawasan terhadap operasionalisasi rumah sakit di Indonesia, menyebabkan orientasi sebagian besar RS hanya mencari keuntungan (laba) dari pasiennya. Kualitas pelayanan, tak dapat dipungkiri, berbanding lurus dengan biaya yang mesti dirogoh dari saku si sakit. Orientasi sosial rumah sakit menjadi sulit ditemukan di tengah kompetisi ketat antar provider (penyedia) pelayanan kesehatan saat ini.
Munculnya klinik-klinik swasta menjadi salah satu pemicu meredupnya praktik perumahsakitan yang benar-benar berorientasi “menyembuhkan” pasiennya. Karena faktor dana, sering kita jumpai orang yang sakit terpaksa pulang sebelum benar-benar sembuh, atau rumah sakit tidak sanggup lagi menutupi kekurangan biaya perawatannya.
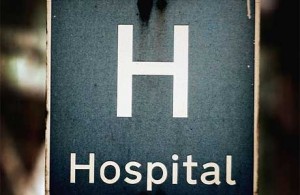
Sedikit positif perkembangan yang ditunjukkan oleh hadirnya program Asuransi Kesehatan bagi Keluarga Miskin (Askes Gakin) beberapa waktu terakhir. Banyak keluarga miskin yang menderita sakit, merasa sangat terbantu dengan adanya Askes Gakin ini.
Namun pada sisi lain, tidak bisa dipungkiri pula, masih terlalu banyak warga miskin lainnya yang sedang sakit, tetapi tidak memiliki akses untuk memiliki kartu peserta Askes Gakin. Cakupan program ini masih sangat terbatas, belum menyentuh semua lapisan masyarakat.
Belum berbicara kualitas pelayanan. Banyak rumah sakit hanya dilengkapi dengan peralatan medik terbatas dengan fasilitas laboratorium yang minim.
Terkadang pasien harus antri berlama-lama untuk menerima pelayanan di poliklinik RS akibat sedikitnya jumlah dokter yang bertugas.
Selain itu, RS kita juga kerap masih bergelut pada “mental model” paramedik yang jauh dari harapan pasien. Sikap yang ramah dan murah senyum, ikhlas membantu pasien serta komunikasi yang melegakan, masih merupakan barang langka dijumpai.
Pada sebagian RS milik pemerintah, untuk pelayanan rawat inap, pasien dan pembesuk harus rela menikmati lingkungan RS yang kotor dan nampak tidak terawat. Sampah di sana-sini tersebar dikerubungi lalat dan tikus.
Fasilitas tambahan seperti air bersih dan kamar mandi kerap sangat terbatas dan cenderung tidak diperhatikan serius kebersihan dan kesehatannya.
Melihat fenomena seperti ini bagaikan kita tidak berada dalam sebuah rumah sakit saja, karena sesungguhnya RS harus dapat memperlihatkan dan mengajarkan budaya hidup bersih dan sehat kepada setiap orang yang berada di dalamnya.
Pelayanan Pasien
DAFTAR ISI
Rumah sakit didirikan sebagai sentral pelayanan kesehatan –terutama kuratif dan rehabilitatif– bagi masyarakat disekitarnya. Paradigma yang dikembangkan dalam tradisi seni pengobatan menjadi karakteristik khas yang seharusnya ada pada setiap aktivitas RS.
Pasien adalah manusia yang setara kedudukannya secara fitrawi dengan dokter dan paramedik lain, sehingga relasi yang terbangun antar mereka mestinya bersifat humanis, bukan eksploitatif. Dalam konteks relasi dokter-pasien ini, berbagai ketimpangan dan ketidakpuasan selalu muncul dan dirasakan oleh kedua belah pihak.
Idealnya, dalam harapan banyak orang, ketika masuk RS kita akan mendapat pengobatan dan perawatan yang baik sehingga dapat segera sembuh dan sehat kembali. Jika pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasiennya tidak menunjukkan hasil memuaskan, maka pasien – dalam keawamannya – sering berpikir bahwa pelayanan RS tersebut tidak bagus.
Kondisi negatif seperti ini semakin mudah tersulut jika “kesan pertama” yang ditunjukkan oleh pihak manajemen RS tidak berkenan di hati pasien yang baru masuk. Padahal, yang diharapkan selain kesembuhan pasien pada aktivitas di RS adalah kepuasan (satisfaction) yang dirasakan oleh semua pihak selama proses pengobatan dan perawatan berlangsung.
Dalam tradisi pengobatan, relasi dokter-pasien mesti memungkinkan terjadinya komunikasi manusiawi yang memberikan kesempatan kepada pasien agar lebih merdeka dan leluasa mengungkapkan perjalanan penyakitnya. Hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang dokter agar dapat mendiagnosa penyakit yang diderita pasiennya.
Komunikasi pasien-dokter hanya dapat berlangsung positif jika kondisi psiologis pasien benar-benar merasa “nyaman”. Nah, kenyamanan ketika masuk RS inilah yang menjadi permasalahan saat ini.
Pada sisi lain, bagi sebagian orang, masuk RS itu menjadi pilihan terakhir jika penyakit yang diderita sudah tidak bisa ditahan lagi. Mereka beranggapan akan sangat beresiko cepat-cepat masuk RS. Selain karena biaya yang cukup mahal, juga rentan dengan resiko terjadinya infeksi nosokomial (penularan penyakit dari RS terhadap orang-orang yang beraktivitas di dalamnya).
Asumsi ini semakin diperparah jika masyarakat pernah trauma atau mengalami pengalaman “tidak mengenakkan” atas pelayanan dokter atau paramedik yang bertugas di RS tersebut. Banyak orang masuk RS ketika penyakitnya sudah sangat parah. Akibatnya penyakit pasien sulit disembuhkan dan tentunya biaya pengobatan/perawatan juga ikut membengkak.
Dalam berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan pengobatan, hak-hak pasien dan hak-hak dokter/paramedik relatif cukup jelas dan mudah dimengerti. Hanya saja, pasien atau keluarga pasien yang masuk di RS cenderung tidak memperhatikan hal ini atau memang tidak tahu sama sekali.
Untuk menyikapi hal ini, maka pihak RS melalui dokter/paramedik yang merawat pasien mestinya memberikan penjelasan dan penyadaran kepada pasien-pasiennya, terutama menyangkut hak mereka atas informasi pra pengobatan dari dokter (informed concent) dan kerahasiaan penyakit yang mereka derita.
Kenyataannya, meskipun UU Praktik Kedokteran telah diterapkan, berbagai indikasi pelanggaran atas hak pasien masih juga mencuat ke permukaan.
Artinya, pihak RS, termasuk dokter dan paramedik yang bekerja di dalamnya, harus menyadari bahwa saat ini masyarakat kita perlahan semakin sadar atas hak mereka mendapatkan “pengobatan yang benar”. Karenanya, otoritas RS mesti giat memperbaiki pelayanan dan “keramahan”-nya terhadap pasien-pasien mereka.
Pemihakan Rumah Sakit
Tak bisa dinafikkan eksistensi sebuah RS sangat dipengaruhi oleh sejauh mana menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Tidak dibenarkan jika RS hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan aspek sosial keberadaanya di masyarakat.
Proporsi 30% tempat tidur untuk kelas III di setiap RS di negara ini pada prinsipnya relatif masih jauh dari memadai. Pun jumlah tersebut tidak akan menguras kas RS dalam-dalam, karena sebagian RS saat ini telah bekerja sama dengan pihak PT Askes untuk pelayanan JPS/Askes Gakin.
Aspek sosial RS sesungguhnya belum lunas terbayar hanya dengan menyediakan tempat tidur kelas III untuk pasien miskin, tetapi mesti diikuti dengan “kesungguhan” dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tidak diskriminatif. Selain itu, pemerintah mesti menegaskan konsekuensi pendirian RS agar selalu harus siap menerima masuknya pasien-pasien gawat darurat yang “tidak mampu” meskipun tidak dilengkapi dokumen miskin dari pemerintah.
Pelayanan medik di RS mestinya dilakukan dengan tidak ada perbedaan antar pasien kelas III dengan pasien kelas “tinggi” lainnya, seperti VVIP, VIP dan Kelas I. Yang seharusnya membedakan antara kelas III dengan kelas “tinggi” lainnya hanyalah faktor fasilitas tambahan dalam ruang perawatan, seperti lemari pendingin, air conditioner, televisi dan kursi-meja tamu.
Dengan demikian, maka “nuansa manusiawi” dalam pelayanan pasien benar-benar dapat dirasakan oleh mereka yang, sesungguhnya tidak pernah menghendaki jatuh sakit hingga diopname di RS.
Kita mengharapkan RS yang belum mencapai “level humanis” seperti yang kita harapkan di atas, dapat segera membenahi manajemen dan menegaskan pemihakannya atas pelayanan yang tidak diskriminitif terhadap semua pasiennya.
Kecuali itu, RS juga mesti secara proporsional menegakkan aspek sosial pengobatan, ketimbang aspek bisnis kapitalisnya, dengan mengutamakan pelayanan di atas urusan pembayaran uang muka. Akhirnya, RS harus benar-benar memerankan dirinya sebagai “rumah untuk menyembuhkan penyakit”, bukan “rumah untuk tetap sakit” atau, “rumah untuk mendapatkan penyakit baru”.
